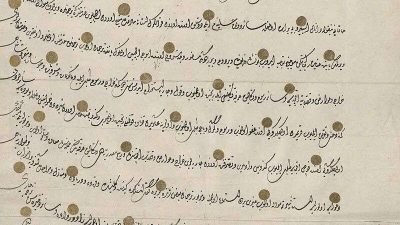Program transmigrasi di Indonesia sejak awal Orde Baru dirancang untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu komponen penting dari program ini adalah pemberian lahan beserta sertifikat tanah kepada transmigran. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah dari pemerintah kepada warga. Namun, dalam praktiknya banyak transmigran yang meninggalkan lahan karena berbagai alasan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana status sertifikat yang masih sah secara hukum?
Sertifikat tanah adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Sertifikat transmigrasi biasanya diberikan setelah proses redistribusi lahan di kawasan transmigrasi selesai. Penerbitannya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi transmigran. Akan tetapi, kepastian hukum ini sering tidak sejalan dengan kepastian pemanfaatan lahan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara status administratif dan kondisi sosial di lapangan.
Banyak transmigran, seperti yang terjadi di kawasan timur Indonesia, memilih kembali ke daerah asal. Penyebabnya beragam, mulai dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung, terbatasnya infrastruktur, hingga bencana alam. Meski demikian, sertifikat tanah yang pernah diberikan tetap tercatat sebagai sah. Inilah yang menimbulkan persoalan: tanah terlantar tetapi secara hukum masih ada pemiliknya. Ketidakhadiran pemilik membuat pengelolaan lahan menjadi tidak optimal.
Tim Ekspedisi Patriot UI Mangoli mencatat keterangan Kepala Desa Modapuhi Trans, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kasus tanah transmigrasi dengan pemilik yang tidak diketahui keberadaannya sering menjadi beban bagi pemerintah daerah. Pihak desa dan kecamatan kerap menghadapi kebingungan ketika ada pihak yang ingin menggarap lahan tersebut. Sertifikat yang sah tidak bisa begitu saja dialihkan tanpa proses hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang menekankan hak milik harus jelas pemegangnya. Ketidakjelasan pemilik dapat menghambat pembangunan desa.
Dari perspektif sosial, tanah transmigrasi yang ditinggalkan bisa memicu konflik horizontal. Masyarakat lokal yang membutuhkan lahan terkadang mencoba memanfaatkan tanah tersebut. Namun, tanpa izin resmi, penggunaan lahan dapat dianggap ilegal. Hal ini memicu potensi sengketa agraria di kemudian hari. Konflik seperti ini telah tercatat di sejumlah wilayah transmigrasi, terutama di Maluku dan Kalimantan.
Pemerintah sebenarnya memiliki mekanisme untuk mengatasi tanah terlantar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah yang tidak dikelola pemiliknya dalam jangka waktu tertentu bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar. Proses ini memungkinkan negara mengambil alih tanah tersebut. Namun, untuk tanah transmigrasi dengan sertifikat sah, penerapannya tidak selalu mudah. Ada aspek keadilan yang harus diperhatikan agar tidak merugikan pemilik sah.
Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa banyak transmigran tidak mengetahui prosedur hukum jika mereka meninggalkan lokasi. Mereka beranggapan bahwa dengan pergi, tanah tersebut otomatis kembali ke negara. Padahal, secara hukum, sertifikat tetap melekat pada nama pemilik. Ketiadaan komunikasi dengan pihak berwenang menambah kerumitan persoalan ini. Akibatnya, data kepemilikan tanah di lapangan sering tidak sesuai dengan dokumen resmi.
Aspek administratif lain yang mempersulit adalah minimnya sistem pemutakhiran data sertifikat. Banyak kantor pertanahan di daerah tidak memiliki mekanisme efektif untuk melacak keberadaan pemilik lama. Digitalisasi data tanah memang mulai dijalankan, tetapi belum merata ke seluruh wilayah transmigrasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi antara data di BPN pusat dan kondisi di lapangan. Akibatnya, lahan menjadi tidak produktif.
Fenomena sertifikat sah dengan pemilik yang tidak diketahui juga memperlihatkan dilema pembangunan. Di satu sisi, pemerintah ingin memanfaatkan lahan untuk kepentingan produktif. Di sisi lain, kepastian hukum harus dijaga agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi. Inilah titik pertemuan antara hukum agraria, kebijakan transmigrasi, dan realitas sosial. Sebuah keseimbangan harus ditemukan agar lahan tidak terabaikan.
Ada contoh di Desa Modapuhi Trans 2, di mana hanya lima keluarga yang bertahan dari puluhan transmigran awal. Sebagian besar kembali ke daerah asal karena seringnya banjir dan keterbatasan infrastruktur. Sertifikat mereka masih ada, tetapi rumah terbengkelai dan tanah dibiarkan kosong. Kondisi ini membuktikan bahwa faktor alam juga berpengaruh besar terhadap keberlanjutan program transmigrasi. Faktor lingkungan tidak bisa diabaikan dalam kebijakan agraria.
Bagi masyarakat lokal, lahan kosong tersebut dianggap mubazir. Mereka sering kali mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi. Salah satu opsi yang diajukan adalah redistribusi tanah kepada warga setempat. Namun, redistribusi memerlukan mekanisme pencabutan hak yang panjang. Tanpa regulasi yang jelas, redistribusi justru bisa memicu sengketa hukum.
Dari perspektif akademis, kasus ini dapat dipandang sebagai fenomena hukum agraria transisional. Sertifikat sah yang tidak digunakan pemiliknya adalah bentuk ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2008), hukum tanah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengakomodasi pluralitas sosial. Hal ini semakin kompleks di wilayah transmigrasi dengan latar belakang penduduk yang beragam. Masalah ini menuntut inovasi kebijakan.
Pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan mediasi dan partisipasi. Salah satunya dengan mendata ulang pemilik sah melalui koordinasi dengan daerah asal transmigran. Proses ini bisa membuka peluang negosiasi untuk menyerahkan atau mengalihkan hak secara sukarela. Dengan begitu, tanah tidak terbengkalai. Pada saat yang sama, hak pemilik tetap dihormati.
Solusi jangka panjang adalah integrasi kebijakan transmigrasi dengan sistem informasi pertanahan digital. Hal ini sesuai dengan program one map policy yang sedang dikembangkan pemerintah. Dengan data yang lebih transparan, keberadaan pemilik sah bisa dipantau lebih baik. Selain itu, tanah yang tidak dimanfaatkan bisa segera diidentifikasi. Langkah ini akan memperkuat tata kelola agraria di kawasan transmigrasi.
Kesimpulannya, sertifikat tanah transmigrasi yang tidak bermasalah secara hukum tetapi pemiliknya tidak diketahui adalah dilema nyata di banyak daerah. Masalah ini mencerminkan ketidaksinkronan antara dokumen hukum, kebijakan pembangunan, dan kenyataan sosial. Penyelesaiannya membutuhkan kombinasi pendekatan hukum, administrasi, dan sosial. Tanpa itu, lahan transmigrasi akan terus menjadi potensi konflik laten. Oleh karena itu, perlu langkah serius agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan masalah baru.
Referensi
Badan Pertanahan Nasional. (2010). Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Jakarta: BPN.
Sumardjono, Maria S.W. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas.
Wiradi, Gunawan. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria: Reformasi Agraria dan Penataan Ruang. Yogyakarta: STPN Press.
Pelzer, Karl J. (1985). Transmigration and Its Implications for Land Use in Indonesia. Honolulu: East-West Center.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (2021). Laporan Evaluasi Program Transmigrasi. Jakarta.